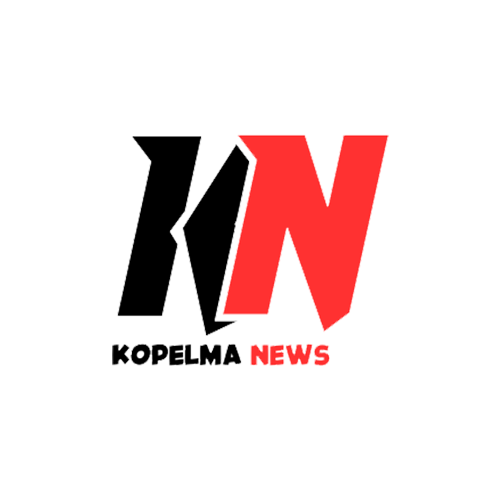Aceh, Kopelmanews.com – Bencana alam yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis mendalam bagi anak-anak usia sekolah. Namun, hingga kini, upaya pemulihan pendidikan pasca bencana masih terlalu berfokus pada pemulihan gedung dan ketertinggalan akademik, sementara aspek pemulihan psikososial siswa kerap terabaikan. Padangsidempuan (24/12/2025)
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi lebih dari 4.500 kejadian bencana alam di Indonesia, dengan jutaan penduduk terdampak, termasuk anak-anak usia sekolah. Sementara itu, laporan UNICEF Indonesia (2022) menunjukkan bahwa anak-anak korban bencana berisiko tinggi mengalami stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, penurunan motivasi belajar, dan gangguan konsentrasi.
Menurut UNICEF (2019) dalam laporan Education in Emergencies, sekolah pasca bencana seharusnya berfungsi sebagai ruang aman (safe space) yang mendukung pemulihan sosial dan emosional anak, bukan semata-mata tempat mengejar ketertinggalan kurikulum. Tanpa dukungan psikososial yang memadai, proses belajar justru berpotensi memperparah trauma yang dialami siswa.
Hal senada ditegaskan dalam Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings yang diterbitkan oleh Inter-Agency Standing Committee (IASC, 2007). Dokumen tersebut menyebutkan bahwa intervensi pendidikan pasca bencana yang mengabaikan kondisi psikologis anak dapat berdampak negatif pada perkembangan jangka panjang, termasuk menurunnya prestasi belajar dan meningkatnya risiko putus sekolah.
Di Indonesia, kerangka hukum sebenarnya telah memberikan dasar yang jelas. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa penanganan bencana mencakup aspek rehabilitasi psikososial, termasuk bagi anak-anak. Selain itu, Satuan Pendidikan sangat perlu menempatkan sekolah sebagai aktor penting dalam pemulihan trauma dan keberlanjutan pembelajaran.
Namun, tantangan di lapangan masih besar. Banyak guru belum dibekali pelatihan dasar tentang dukungan psikososial (psychosocial support), sementara layanan konselor sekolah di daerah terdampak bencana masih sangat terbatas.
Oleh karena itu, pemulihan pendidikan pasca bencana perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih holistik. Sekolah tidak hanya membutuhkan ruang kelas yang layak, tetapi juga guru yang mampu menciptakan suasana aman, rutinitas belajar yang menenangkan, serta aktivitas pembelajaran yang membantu anak mengekspresikan emosi dan membangun kembali rasa percaya diri. Tanpa menjadikan pemulihan psikososial sebagai prioritas, pendidikan pasca bencana berisiko kehilangan esensinya sebagai sarana perlindungan dan pemulihan anak. Sekolah seharusnya menjadi titik awal bagi anak-anak untuk bangkit, bukan sekadar kembali duduk di bangku kelas dengan trauma yang belum terselesaikan.