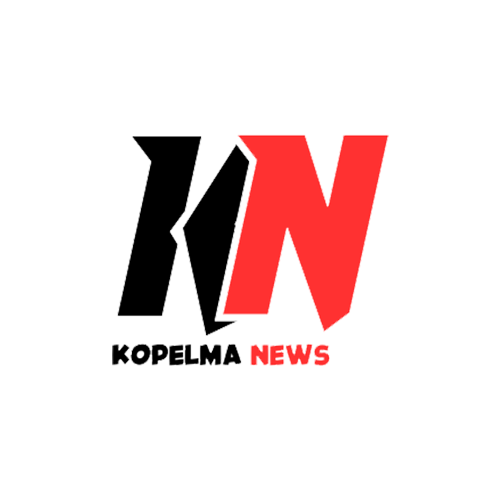Aceh, Kopelmanews.com – Sejarah Islam kerap dibicarakan dengan nada nostalgia: masa keemasan, kejayaan peradaban, dan kepemimpinan ideal yang seolah tanpa cela. Dari mimbar ke media sosial, masa lalu sering dihadirkan sebagai jawaban atas semua problem umat hari ini. Namun pertanyaan penting jarang diajukan secara jujur: mengapa umat Islam begitu gemar meromantisasi sejarahnya sendiri? Padahal
Salah satu sebab utamanya adalah pengalaman panjang keterpurukan politik dan ekonomi di dunia Muslim modern. Ketika realitas hari ini diwarnai konflik, ketertinggalan, dan ketidakadilan global, masa lalu tampil sebagai ruang aman psikologis. Sejarah tidak lagi dibaca sebagai pelajaran, melainkan sebagai pelarian. Romantisme menjadi obat penenang kolektif bagi luka sejarah yang belum sembuh.
Romantisasi juga lahir dari cara sejarah Islam diajarkan. Sejak dini, umat lebih sering diperkenalkan pada figur-figur besar yang nyaris sempurna, sementara konflik internal, perbedaan pendapat, dan kegagalan politik disingkirkan dari narasi. Akibatnya, sejarah berubah menjadi kisah heroik, bukan medan pergulatan manusiawi. Padahal, para tokoh Islam klasik justru besar karena kemampuan mereka mengelola perbedaan dan krisis, bukan karena hidup di zaman tanpa masalah.
Ada pula faktor teologis yang kerap disalahpahami. Keberhasilan generasi awal Islam sering dipersepsikan sebagai bukti kemurnian iman, sementara kemunduran hari ini dianggap akibat menjauh dari masa lalu. Logika ini sederhana, tetapi berbahaya. Ia menutup ruang kritik dan pembaruan, karena setiap upaya kontekstualisasi mudah dicap sebagai penyimpangan dari tradisi ideal.
Yang jarang disadari, romantisasi sejarah sering berfungsi sebagai alat politik. Masa lalu dipilih, dipoles, dan disederhanakan untuk membenarkan agenda kekuasaan di masa kini. Sejarah dijadikan slogan, bukan cermin. Dalam kondisi ini, umat tidak diajak berpikir, melainkan diajak bernostalgia sebuah kondisi yang membuat sejarah kehilangan daya emansipatorisnya.
Padahal, sejarah Islam yang paling jujur justru penuh dinamika: perdebatan mazhab, konflik politik, kesalahan pemimpin, hingga kritik keras dari ulama terhadap penguasa. Inilah sejarah yang manusiawi, yang seharusnya memberi keberanian untuk menghadapi kenyataan, bukan menghindarinya.
Romantisasi sejarah bukan masalah selama tidak menggantikan nalar kritis. Masalah muncul ketika masa lalu dijadikan tempat bersembunyi dari tanggung jawab masa kini. Umat Islam tidak kekurangan sejarah gemilang, tetapi sangat membutuhkan keberanian untuk membaca sejarah secara dewasa menerima kebesaran sekaligus kegagalannya. Barangkali, umat Islam tidak perlu terus-menerus bertanya kapan masa kejayaan itu akan kembali. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa pelajaran paling jujur dari sejarah yang berani kita terapkan hari ini?