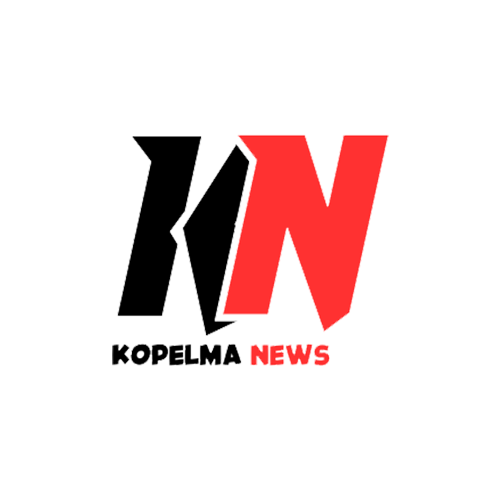Aceh, kopelmanews.com – Sekolah dipahami sebagai simbol kesempatan. Ketika sebuah gedung berdiri, kita menganggap pendidikan telah tersedia dan tugas telah selesai. Namun, bagi anak berkebutuhan khusus belum tentu hadirnya akses yang benar ramah. Ada jarak antara sekolah yang “ada” dan sekolah yang benar-benar “dapat diakses”. Di sinilah persoalan infrastruktur bagi anak Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi penting untuk dibicarakan sebagai refleksi bersama. Banda Aceh (21/12/2025)
Bagi anak SLB, ruang belajar bukan sekadar kelas dan papan tulis. Akses fisik seperti jalur landai, ruang terapi, pencahayaan yang memadai, hingga alat bantu belajar menjadi bagian dari kebutuhan dasar yang menentukan keberlangsungan proses belajar. Ketika fasilitas ini tidak tersedia atau tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka, proses belajar berubah menjadi tantangan yang melelahkan, bahkan sebelum pelajaran dimulai. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang tumbuh justru dapat terasa membatasi.
Sering kali, infrastruktur dipahami sebatas bangunan yang kokoh dan tampak layak dari luar. Padahal, bagi anak SLB, detail-detail kecil justru menentukan kenyamanan dan kebermaknaan belajar. Tangga tanpa pegangan, ruang kelas yang bising, atau tata ruang yang sempit dapat menjadi penghalang yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang.
Akses yang tidak ramah kerap hadir dalam bentuk yang sederhana, namun berdampak besar terhadap pengalaman belajar anak. Hambatan semacam ini jarang disadari karena tidak semua orang mengalaminya secara langsung, sehingga ia kerap luput dari perhatian.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan akses bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal cara pandang. Ketika anak SLB diposisikan sebagai kelompok “khusus”, kebutuhan mereka kerap dianggap tambahan, bukan keharusan. Akibatnya, pemenuhan akses sering berada di urutan belakang, seolah dapat ditunda tanpa konsekuensi serius. Padahal, setiap penundaan akses berarti menunda kesempatan anak untuk belajar dengan aman dan layak.
Padahal, infrastruktur yang ramah bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan bentuk penghormatan terhadap martabat anak. Lingkungan sekolah yang dapat diakses dengan aman dan nyaman memberi pesan bahwa mereka diakui sebagai bagian utuh dari dunia pendidikan. Sebaliknya, keterbatasan akses secara tidak langsung mengajarkan bahwa mereka harus menyesuaikan diri dengan sistem yang tidak dirancang untuk mereka. Pesan semacam ini sering kali hadir diam-diam, tetapi dampaknya bertahan lama.
Perhatian terhadap akses SLB juga berkaitan erat dengan gagasan pendidikan inklusif. Inklusivitas tidak cukup diwujudkan melalui kebijakan tertulis atau slogan yang terdengar indah, tetapi perlu hadir dalam wujud nyata yang dapat dirasakan sehari-hari. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat diperlukan agar SLB tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga berfungsi optimal sebagai ruang belajar yang manusiawi dan berpihak pada kebutuhan anak.
Membicarakan infrastruktur SLB bukan berarti meniadakan peran sekolah umum atau memperlebar jarak antar sistem pendidikan. Sebaliknya, isu ini mengingatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya.
Pendidikan yang adil tidak memaksa semua anak berada dalam kondisi yang sama, tetapi memastikan setiap perbedaan mendapatkan ruang yang layak untuk berkembang. Pada akhirnya, sekolah yang benar-benar hadir bukan hanya yang memiliki gedung dan papan nama. Ia adalah sekolah yang menyediakan akses, rasa aman, dan kesempatan belajar yang setara.
Selama akses bagi anak SLB masih belum sepenuhnya ramah, maka tugas kita bersama adalah terus mengingatkan bahwa pendidikan bukan sekadar ada, tetapi harus dapat dijangkau oleh semua. Sebab pendidikan yang adil tidak diukur dari berapa banyak sekolah yang berdiri, melainkan dari sejauh mana setiap anak dapat mengaksesnya dengan bermartabat.