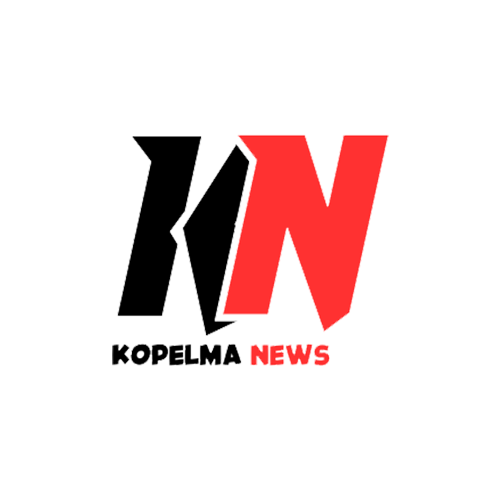Aceh, Kopelmanews.com – Suasana ujian sekolah biasanya lekat dengan gambaran barisan meja yang rapi dan keheningan yang mencekam. Namun, standar tersebut terasa berbeda ketika kita melangkah masuk ke The Nanny Children Center (TNCC). Di sekolah yang mengusung konsep inklusi ini, masa ujian bukan sekadar periode evaluasi akademik, melainkan sebuah fragmen kehidupan yang memperlihatkan dinamika mental yang luar biasa unik antara siswa dan pendidiknya.
Kehadiran mahasiswa Psikologi untuk melakukan observasi di TNCC bertepatan dengan momen ujian, sebuah waktu yang sangat sensitif bagi setiap pelajar. Di sini, ujian tidak dimulai dengan bunyi bel yang menuntut ketertiban mutlak, melainkan dimulai dengan upaya para pendidik untuk menciptakan rasa aman bagi siswa. Pengamatan awal menunjukkan bahwa persiapan mental siswa menjadi fokus utama sebelum lembar soal dibagikan ke meja mereka masing-masing.
Fenomena paling mencolok yang tertangkap dalam pengamatan ini adalah resistensi atau penolakan siswa terhadap proses ujian itu sendiri. Ditemukan beberapa siswa yang secara terang-terangan menunjukkan keengganan untuk menyentuh kertas ujian yang telah disediakan. Beberapa di antaranya memilih untuk memalingkan wajah, terdiam seribu bahasa, atau bahkan menjauhkan kursi dari meja ujian sebagai bentuk protes tanpa suara terhadap situasi yang sedang dihadapi.
Pemandangan ini menjadi kontras tajam dengan sekolah formal pada umumnya, di mana ketakutan akan nilai buruk biasanya memaksa siswa untuk patuh pada sistem. Di TNCC, kita melihat sebuah realitas di mana kejujuran emosional siswa lebih tampak ke permukaan. Penolakan tersebut bukanlah sebuah bentuk kenakalan, melainkan ekspresi dari kesulitan yang sedang mereka alami dalam menghadapi tekanan formalitas ujian yang berbeda dari kegiatan belajar harian.
Melalui kacamata psikologi, keengganan untuk mengikuti ujian ini seringkali berakar pada kecemasan terhadap perubahan rutinitas (disrupsi rutin). Bagi siswa dengan kebutuhan khusus, ujian menciptakan lingkungan yang tidak biasa—ada aturan yang lebih ketat dan ekspektasi yang meningkat secara mendadak. Kondisi ini dapat memicu beban sensorik dan kognitif yang besar, sehingga menarik diri atau “mogok” menjadi mekanisme pertahanan diri (coping mechanism) untuk melindungi diri dari rasa frustrasi.
Lebih jauh lagi, ketidakmampuan siswa untuk menyuarakan rasa takut atau kebingungan terhadap instruksi soal yang abstrak membuat mereka mengekspresikannya melalui perilaku non-verbal. Mereka tidak “malas”, melainkan sedang berjuang mengelola energi mental yang terkuras habis hanya untuk memahami situasi ujian. Memahami bahasa di balik penolakan ini adalah kunci penting bagi siapapun yang ingin mendalami dunia pendidikan inklusi.
Menariknya, suasana di kelas tetap terjaga kondusif meskipun ada siswa yang menunjukkan penolakan. Tidak ada suara keras dari guru yang menuntut kepatuhan, atau ancaman nilai yang membayangi. Para pendidik di TNCC menunjukkan pendekatan yang sangat sabar dengan menggunakan teknik coaxing atau bujukan lembut. Mereka berusaha melakukan validasi atas perasaan tidak nyaman yang sedang dirasakan anak sebelum perlahan mengarahkan mereka kembali pada tugasnya.
Observasi ini membuktikan bahwa keberhasilan proses belajar-mengajar di lingkungan inklusif tidak diukur dari seberapa cepat soal diselesaikan, melainkan dari seberapa aman siswa merasa untuk tetap berada di dalam kelas. Guru berperan sebagai jembatan emosional, memastikan bahwa tantangan akademik tidak merusak stabilitas mental sang anak. Keberanian siswa untuk tetap duduk di kursi ujian, terlepas dari apakah kertasnya terisi penuh atau tidak, sudah dianggap sebagai sebuah kemenangan kecil.