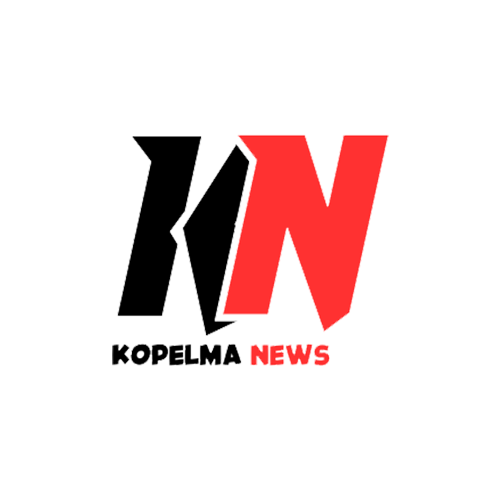Aceh, Kopelmanews.com – Media sosial yang dulu dijanjikan membawa kedekatan, kini justru menghadirkan jarak dan luka. Di balik layar-layar kecil itu, banyak jiwa muda yang tenggelam tanpa suara. Di layar ponsel, segalanya tampak sederhana seperti menulis komentar, menekan tombol kirim, lalu melanjutkan gulir tanpa berpikir panjang. Namun bagi seorang remaja berusia lima belas tahun di Australia, satu unggahan palsu di media sosial menjadi titik akhir hidupnya. Ia bernama Tilly Rosewarne, putri dari Emma Mason seorang ibu yang kini menjadi simbol perjuangan melawan kekejaman yang bersembunyi di balik layar.
Foto palsu Tilly disebarkan melalui media sosial. Dari situ, datang gelombang ejekan, hinaan, dan pelecehan. Di dunia yang tampak hanya berupa piksel dan teks, ia merasa terpojok, terisolasi, hingga akhirnya memilih jalan paling tragis yaitu mengakhiri hidupnya sendiri. Emma Mason kini berdiri di panggung dunia, berbicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, memperjuangkan batas usia penggunaan media sosial agar tidak ada anak lain yang mengalami nasib serupa. Australia pun akhirnya menetapkan aturan baru: melarang anak di bawah 16 tahun membuat akun media sosial tanpa izin orang tua.
Tragedi ini mengguncang kesadaran dunia. Ternyata, ruang yang kita sebut “maya” tidak pernah benar-benar maya. Ia hidup dan bekerja di antara kita, menyentuh batin, menembus batas daging dan pikiran. Apa yang terjadi di dunia digital sesungguhnya memiliki bobot yang sama nyata dengan peristiwa di dunia fisik. Ketika kata-kata kejam diketikkan, rasa sakit itu tidak berhenti di layar ia menembus hati manusia yang membacanya. Mungkin kesalahan besar generasi kita menganggap dunia digital hanyalah permainan, padahal di sana hidup jiwa-jiwa yang sungguh ada.
Kematian Tilly membuat kita menatap ulang cermin zaman. Betapa banyak di antara kita yang sibuk membangun citra di dunia daring, tapi kehilangan kesadaran bahwa di balik setiap akun ada manusia yang bisa terluka. Kita berinteraksi dengan nama pengguna, bukan dengan manusia. Kita menganggap hinaan hanyalah teks, bukan tikaman. Padahal, di balik satu kalimat, ada napas seseorang yang bisa berhenti karena putus asa.
Kita hidup di masa ketika informasi datang lebih cepat daripada empati. Media sosial menjanjikan kebebasan berbicara, namun sering gagal menanamkan tanggung jawab. Dalam dunia di mana setiap orang bisa menjadi penyiar, siapa yang memastikan kebenaran dan kebaikan dari apa yang disiarkan? Kita sering percaya pada apa yang viral, bukan pada apa yang benar. Kebenaran diukur dari seberapa banyak orang menyukai, bukan dari seberapa dalam maknanya. Inilah zaman di mana “pengetahuan” bukan lagi hasil pencarian, melainkan hasil klik.
Kasus Tilly menunjukkan betapa mudahnya kebenaran diputarbalikkan. Sebuah foto palsu bisa dipercaya seolah nyata. Sebuah rumor bisa menjelma kenyataan sosial hanya karena diulang berkali-kali di media. Di titik ini, kita tidak hanya kehilangan kontrol atas informasi, tapi juga kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang sekadar “tampak benar”. Dunia digital menciptakan kabut pengetahuan, di mana setiap orang berbicara tanpa mendengar, beropini tanpa memahami.
Namun tragedi bukan hanya soal salah dan benar, melainkan soal nilai. Apa yang membuat seseorang tega menertawakan kesedihan orang lain? Apa yang membuat banyak orang lebih memilih menonton daripada menolong? Di dunia digital, jarak antara empati dan apati begitu tipis. Kita bisa menulis “turut berduka” pada satu unggahan, lalu menertawakan unggahan lain dalam detik yang sama. Kita kehilangan rasa hormat pada kesedihan, karena kesedihan pun kini menjadi konten.
Inilah sebabnya, pembatasan media sosial di Australia bukan sekadar kebijakan teknologi, melainkan upaya memulihkan nilai-nilai kemanusiaan. Negara itu sadar bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab hanya melahirkan kekacauan. Anak-anak belum siap memikul beban dunia digital yang begitu kejam. Mereka membutuhkan ruang untuk tumbuh dalam dunia nyata terlebih dahulu, sebelum dihadapkan pada dunia maya yang bisa menghancurkan dengan satu klik.
Kebijakan tersebut memang menimbulkan perdebatan. Sebagian menuduh pemerintah membatasi kebebasan berekspresi. Tapi bukankah kebebasan sejati adalah kebebasan yang disertai kesadaran akan akibatnya? Kita boleh berbicara, tapi tidak untuk melukai. Kita boleh berteknologi, tapi tidak untuk merendahkan martabat manusia. Kebebasan tanpa tanggung jawab hanyalah bentuk lain dari kejahatan yang dibungkus dengan hak.
Dari tragedi Tilly, kita seharusnya belajar bahwa teknologi bukan sekadar alat, ia mencerminkan nilai-nilai kita. Media sosial diciptakan untuk mendekatkan manusia, tetapi mengapa justru membuat kita saling menjauh? Kita perlu menata kembali cara berpikir kita tentang dunia digital bukan sekadar menguasainya, tetapi memahami esensi kemanusiaan di dalamnya. Teknologi tanpa budi pekerti hanyalah mesin tanpa jiwa. Dan manusia tanpa etika di dunia digital, hanyalah algoritma yang berwajah manusia.
Di Indonesia, kasus serupa sudah sering terjadi, meski jarang mendapat perhatian luas. Banyak anak muda mengalami tekanan mental karena ejekan di grup daring, pesan anonim, atau penyebaran foto pribadi. Sebagian memilih diam, sebagian hilang semangat, sebagian lain pergi selamanya. Kita tak bisa lagi berpura-pura bahwa ini hanya masalah “mental yang lemah”. Ini adalah masalah sosial, masalah budaya, dan masalah moral.
Sekolah harus menjadi ruang pertama untuk menanamkan literasi digital bukan hanya cara menggunakan gawai, tetapi cara berperilaku di dalamnya. Orang tua harus hadir, bukan sekadar membelikan ponsel, tetapi menemani anak memahami dunia yang mereka masuki. Pemerintah harus hadir, bukan hanya saat tragedi, tetapi sebelum tragedi terjadi. Dan kita semua, para pengguna, harus sadar bahwa setiap kata yang kita tulis punya daya: membangun, atau menghancurkan.
Dunia maya adalah cermin hati manusia. Jika yang kita pantulkan adalah kebencian, maka yang kembali hanyalah kehancuran. Tapi jika yang kita pancarkan adalah kasih dan empati, dunia digital bisa menjadi ruang yang menumbuhkan. Kita tidak perlu mematikan internet, tapi kita harus menyalakan nurani.
Emma Mason kehilangan putrinya, namun ia tidak kehilangan keberaniannya. Suaranya kini menggema di forum dunia, membawa pesan bahwa teknologi seharusnya berpihak pada kehidupan, bukan kematian. Pesan itu seharusnya sampai juga kepada kita bahwa menjaga anak-anak di dunia digital bukan sekadar tugas negara, melainkan tanggung jawab bersama sebagai manusia. Pada akhirnya, dunia maya hanyalah cermin dari dunia nyata. Jika kita gagal menjadi manusia di dalamnya, maka yang runtuh bukan hanya sistem digital, tapi juga nurani kita sendiri.